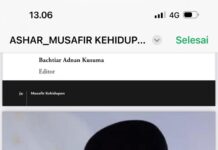Kolom Hafid Abbas
Hanya sekitar 11 jam 35 menit, setelah Hiroshima dibom oleh pasukan AS pada 6 Agustus 1945, tepatnya pada jam 7:50 malam, Kaisar Hirohito menerima laporan dari Panglima Angkatan Laut Jepang (Navy Ministry) bahwa kini Horoshima sudah hancur, rata dengan tanah.
Pada 8 Agustus di malam hari, Hirohito menegaskan bahwa keadaan tidak memungkinkan lagi Jepang meneruskan peperangan dengan pengakuan kekalahan di pihaknya.
Para jenderal tersebut kemudian menegaskan kepada Kaisar bahwa mereka masih mampu menyelamatkannya dari serangan mana pun. Kaisar mengatakan bahwa Jepang telah kalah dikarenakan kita tidak belajar. Kalian para jenderal dan tentara Jepang boleh menguasai persenjataan dan strategi perang, tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bom yang telah dijatuhkan AS.
Hirohito kemudian menegaskan bahwa Jepang tidak akan mampu mengejar AS jika tidak belajar. Karenanya, ia kemudian menginstruksikan para jenderalnya untuk menghitung berapa lagi jumlah guru yang selamat dan mengumpulkan mereka yang tersisa itu di seluruh pelosok Jepang. Sebab, kepada para gurulah seluruh rakyat Jepang kini harus bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan (thejapantimes, 09/09/2014).
Diperkirakan mencapai 146 ribu warga sipil dan 20 ribu lebih pasukan Jepang tewas di Hiroshima, 246 ribu warga sipil dan 80 ribu tentara tewas di Nagasaki pada pemboman kedua (9 Agustus), dan jutaan warga lainnya yang cacat seumur hidup karena radiasi, Jepang bangkit dengan membenahi persoalan gurunya. Kaisar kemudian mendapatkan laporan bahwa masih tersisa 45 ribu guru yang selamat di seluruh Japang. Kaisar berpesan kepada mereka bahwa keselamatan dan kejayaan Jepang di masa depan bukan di tangan para jenderal dan kekuatan persenjataannya tetapi di pundak para guru.
Karenaya, sejak 1949, semua guru di semua jenjang pendidikan untuk semua jenis matapelajaran harus bersertifikat untuk memastikan kemampuan profesionalnya(MEXT 2010).
Hasilnya, kini Jepang telah menjadi negara maju secara ekonomi, politik, pertahanan keamanan, berteknologi tinggi yang sejajar dengan negara mana pun di pelanit ini.
Jika Indonesia hendak memetik pelajaran dari Jepang untuk bangkit menjadi negara maju, damai, adil dan sejahtera pada 2045, di hari kemerdekaannya yang ke-79 ini, kelihatannya petajalan pembenahan persoalan guru berkisar pada hal-hal berikut.
Pertama, pada 2045, secara statistik Indonesia dipredikasi akan berpenduduk 350 juta jiwa. Seperti apa tatanan kehidupan penduduk Pulau Jawa pada 2045 yang luasnya hanya sekitar 6% dari seluruh wilayah tanah air jika tetap harus dihuni 60-70% dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 2020). Bukankah pada 1985, Jawa telah tercatat sebagai salah satu pulau terpadat di dunia.
Sulit dibayangkan akan bagaimana tekanan demografis ini dan gejolak-gejolak sosial yang akan ditimbulkannya untuk menghasilkan guru yang profesional yang akan menyiapkan generasi emas yang unggul di pergaulan global pada 21 tahun ke depan.
Kedua, pada 2045, lingkup kawasan ASEAN akan menyatu menjadi a single community of nations, secara ekonomi, politik, pertahanan dan sosial budaya. Bahkan, pada 2030, akan terwujud ASEAN Borderless Economic Community yang menandai hubungan kerjasama ekonomi antarnegara-negara anggota ASEAN akan lebih menyatu. Seperti apa wajah pendidikan Indonesia pada kehidupan masyarakat tunggal itu kelak.
Apakah, Indonesia masih akan tetap membiarkan jutaan penduduknya menjadi buruh kasar berupah rendah di negara-negara tetangganya, dan membiarkan melimpahnya tenaga kerja kasar China ke sini. Jika negara akan hadir untuk melindungi dan memuliakan kehidupan mereka, seperti apa tata kelola pendidikan dan seperti apa pola pengadaan guru yang harus dipersiapkan hari ini.
Ketiga, pada 2045 diperkirakan kesenjangan sosial akan semakin melebar jika tidak segera diatasi. Dilaporkan oleh Global Wealth Databooks (2016), Indonesia berada pada urutan ke empat terburuk di dunia tingkat kesenjangan kaya-miskin, berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Bahkan diungkapkan oleh Oxfam (2017) bahwa kekayaan empat orang kaya Indonesia setara dengan jumlah kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin negeri ini. Dilaporkan pula oleh Kompas pada 15 dan 16 Maret 2018 bahwa terdapat hanya beberapa warga negara yang telah menguasai hampir 50 juta hektar lahan atau setara dengan 741 kali luas Jakarta.
Seperti apa wajah pendidikan dan pengadaan guru atas makin melebarnya kesenjangan sosial itu. Dapatkah dihasilkan guru yang menjadikan pendidikan sebagai alat pemerata (the best equalizer) untuk mengangkat kehormatan dan martabat warga negara yang tertinggal.
Menatap ke Depan
Menuju Indonesia Emas 2045, untuk membenahi persoalan guru dari hulu, tata kelola LPTK sebagai penghasil guru hari ini perlu dihadapatkan pada beragam kenyataan berikut.
Pertama, secara statistik, saat ini sudah terdapat 423 LPTK sebagai penghasil guru dan tenaga kependidikan. Dari jumlah itu, 12 eks-IKIP, 34 FKIP universitas, dan 377 LPTK swasta (Kemristekdikti 2020). Dari jumlah itu yang sudah terakreditasi A hanya 18, dan 81 terakreditasi B, selebihnya 324 LPTK tidak terakreditasi atau terakreditasi rendah (Dikti, 2019).
Dengan data ini, terlihat perlu dilakukan rasionalisasi jumlah LPTK, termasuk melakukan penutupan secara bertahap (phasing out) bagi yang belum memenuhi syarat. Demikian pula, rasionalisasi penerimaan mahasiswa calon guru perlu dilakukan.
Sebab, 77 persen LPTK yang belum terakreditasi atau terakreditasi rendah ini umumnya swasta, terlihat terus-menerus merekrut dan meluluskan mahasiswa calon guru tanpa kendali sehingga setiap tahun terdapat kelebihan sekitar 200 ribu calon guru baru yang kebanyakan direkrut menjadi guru honorer juga di sekolah-sekolah swasta (kompasiana.com, 01/04/2024).
Kedua, untuk memastikan kualitas, sesuai amanat pasal 23 UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah dapat memberlakukan pendidikan calon guru secara berasrama. Ini layak dimulai pada LPTK eks-IKIP atau pada LPTK yang telah berakreditasi unggul dengan, misalnya hanya menerima 20% lulusan SLTA terbaik untuk dipersiapkan menjadi guru seperti yang dilakukan Finlandia.
Jika setiap tahun diperlukan hanya 60 ribu calon guru baru, ke-18 LPTK yang telah berakreditasi unggul perlu diberi kuota penerimaan calon mahasiswa baru yang lebih besar, dan secara selektif, terutama dari LPTK eks-IKIP dapat memberlakukan pendidikan guru secara berasrama.
Ketiga, pembangunan Sekolah Inpres di era Presiden Soeharto terlihat telah amat berhasil tidak hanya memperluas akses pendidikan kepada anak usia pendidikan dasar, tetapi juga menurunkan angka kemiskinan karena ditempatkan di daerah berpenghasilan rendah dan padat penduduk di desa atau di kota. Selain itu, untuk menuntaskan persoalan kemiskinan diberlakukan pula program Kelompok Belajar (Kejar) A1-A100 untuk peningkatan kualitas hidup.
Hingga 1993/1994, tercatat sekitar 150 ribu unit SD Inpres telah dibangun, dan telah ditempatkan pula lebih satu juta guru Inpres di sekolah-sekolah tersebut. Angka Buta Huruf usia 10-45 tahun juga telah berhasil diturunkan dari 39,1% (80 juta jiwa) pada 1971 ke 15,9% pada 1990. Atas keberhasilan itu, ikut menyaksikan, di Istana Negara pada 19 Juni 1993, UNESCO memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto The Avicenna Award.
Mengagumkan pula, pada 2019, tercatat tiga ekonom AS mendapat Hadiah Nobel yakni Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer, karena lewat penelitiannya telah mengangkat betapa keberhasilan Soeharto meluaskan akses pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekolah lewat sekolah inpresnya, dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Bahkan, dalam artikelnya “Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Usual Policy Experiment” (2000), peraih nobel Duflo mencatat, program SD Inpres Soeharto merupakan salah satu program pembangunan sekolah terbesar di dunia yang pernah tercatat dalam sejarah itu.
Terakhir, menuju Indonesia Emas 2045, mari merenung memaknai Hari Kemerdekaan dengan tetap merawat beragam kesuksan Indonesia di masa lalu, dan terbuka belajar dari bangsa-bangsa yang lebih maju. Bagaimana misalnya, di masa lalu, Malaysia yang mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk memajukan pendidikannya, kini sudah jauh lebih maju dari Indonesia. Mengapa pula 89% Vietnam yang telah dilanda perang selama 50 tahun, kini kemajuan pendidikan sains dan matematikanya tercatat di PISA 2022 terbaik ke-8 di antara 73 negara peserta, dan Indonesia berada di urutan kedua terendah di dunia, dst. Mengapa pula masih terdapat 89% anak SD, 50% siswa SMP dan 40% siswa SLTA di sejumlah kabupaten di Papua Selatan yang belum bisa membaca dan menulis (WVI,8/12/2022). Lalu, mengapa pula anggaran pendidikan 500-600 triliun habis setiap tahun dengan tidak ada manfaatnya bagi peningkatan mutu pendidikan di tanah air.
Penulis Guru Besar UNJ dan Dewan Pakar KKSS