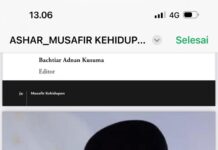Kolom Imran Duse
Dewasa ini, teknologi digital telah hadir menjadi bagian penting dari kehidupan umat manusia. Dari bangun pagi hingga jelang terlelap di malam hari, gawai senantiasa membersamai manusia menjalankan aktivitasnya. Bahkan, sebagian menjalankan aktivitasnya justeru di dalam mesin baru itu.
Terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat. Dari PSBB hingga PPKM Level 4, larangan mudik hingga makan gak boleh lebih 20 menit; semuanya dilalui dengan mengamaikan jaringan internet. Melalui layar cerdas itu, anak-anak bersekolah; emak-emak berbelanja; mahasiswa rapat; dan politisi berjanji. Pendek kata, nyaris tak ada aspek kehidupan manusia yang tak terpaut dengannya.
Dalam keterpautan itu, setiap orang kini bisa menjadi konsumen sekaligus produsen informasi –bahkan dalam waktu bersamaan. Seringkali tanpa referensi dan verifikasi, dengan bebas sebuah berita dilayangkan ke dunia maya. Dan hoaks pun mengintip, bersiap menebar kecurigaan dan purbasangka.
Sebarannya dapat ditangkap melalui media sosial, sebagai sebuah fenomena baru yang dijinjing internet. Semenjak kemunculan Friendster (2002) dan disusul Facebook (2005). Fenomena itu lalu ditopang oleh kehadiran BlackBerry sebagai ponsel cerdas pertama dengan fasilitas push mention media sosial yang menyahajakan pengguna berselancar di lapak maya.
Dan hanya dalam waktu singkat, BalckBerry pun telah menjadi masa lalu. Digantikan ponsel pintar berbasis android, yang tak lelah memperbarui fitur dan menstimulasi kemampuannya, namun dengan harga yang semakin terjangkau. Ini menaruh andil dalam mendongkrak laju pertumbuhan media sosial.
Dengan kata lain, sebuah peradaban berbasis mesin baru yang disesaki artifisial intelligent (AI) telah lahir. Melaluinya, manusia terhubung secara realtime, kendati terpisah jarak-terjauh. Hingga beberapa waktu, perkembangan itu cukup mengimpikan. Sampai kemudian banyak yang menyadari, bahwa sebuah potensi ekploitasi sedang disemai –dan akan tumbuh menjadi ekses ekosistem komunikasi ini.
Setel Ulang
Ronald J. Deibert adalah salah satu dari sedikit yang menyadari potensi itu. Pakar keamanan digital ini secara intens mencermatinya dan kemudian memaparkan pengaruh internet terhadap politik, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan, dalam bukunya yang terbit akhir tahun lalu: “Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society”.
Melalui Citizen Lab –sebuah lembaga penelitian keamanan digital terkenal–, ia melakukan riset tentang hal ini dalam rentang waktu dua decade. Hasilnya disajikan dalam buku setebal 419 halaman tersebut. Lembaga yang didirikan dan dipimpin langsung Deibert itu memaparkan dampak ekosistem komunikasi terhadap civil society.
Deibert juga menggali bagaimana ketergantungan pada media sosial menciptakan tekanan besar pada alam dan lingkungan. Untuk memerangi praktik otoriter, degradasi lingkungan, dan konsumerisme elektronik yang merajalela, ia mendesak pembatasan pada platform teknologi dan pemerintah guna merebut kembali internet untuk kepentingan masyarakat sipil.
Peneliti kelahiran Kanada ini dengan gamblang membongkar lintasan kehidupan digital yang kian mengkhawatirkan. Menurutnya, manusia saat ini berisiko kehilangan privasi akibat penerapan kontrol teknologi digital. Setidaknya ada empat hal yang disorot Deilbert.
Pertama, jika pendapatan media cetak dan penyiaran bertumpu kepada kepada pelanggan dan advertorial, maka media sosial tidaklah demikian. Kendati dalam sejumlah kasus kita juga menyaksikan media sosial melakukan hal tersebut.
Sumber pendapatan media sosial amat bergantung pada akumulasi, analisis, dan komersialisasi data pribadi dari pengguna. Tidak mengherankan jika media sosial berkembang menjadi “mesin” yang tanpa henti menggali lebih dalam dan secara terus menerus memasuki kehidupan pribadi kita. Dengan kemampuan algoritma komputer dan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence -Ai), media sosial tanpa henti mengetuk akun media sosial layar kita dan mengaitkan sejumlah sensor yang mampu melacak pergerakan, percakapan, lokasi, dan juga emosi kita –bahkan pada waktu sedang tidak digunakan.
Deibert juga mengkritisi perjanjian term-of-service yang menurutnya seringkali disepelekan pengguna akibat ilusi pilihan dan kontrol yang begitu padat. Aplikasi dan platform tersebut memang didesain sedemikian rupa, sehingga –seperti dikatakan tadi– kerap disepelekan oleh pengguna.
Kedua, adalah kemampuan aplikasi dan platform media sosial untuk mengekstrak sebanyak mungkin data pengguna. Sehingga dengan mengolah data itu membuat pengguna ketagihan ke aplikasi dan platform tersebut. Semakin lama kita aktif menggunakan layanan itu, maka semakin banyak data yang mereka kumpulkan. Dengan bantuan Ai, perusahaan media sosial terus memoles lingkaran kecanduan itu sehingga relevan dengan preferensi, bias, dan kecemasan setiap individu.
Media sosial pun telah menjadi “mesin kecanduan beracun” yang secara beruntun memuntahkan gosip, disinformasi, dan rasisme. Media sosial dengan mudah mengobarkan perpecahan identitas dan memungkinkan massa yang marah dimobilisasi lewat viralitas baru.
Ketiga, kendati ada yang memandang media sosial sebagai “teknologi pembebasan” (dalam implikasinya terhadap kebebasan dan demokrasi), namun di sisi lain, media sosial juga memberi ruang bagi despotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Melaluinya, Autokrat mengontrol informasi hingga “menggagalkan oposisi politik dan perbedaan pendapat” dan untuk melacak dan menangkap para pengkritik rezim.
Menurut Deibert, di seluruh dunia, tak terhitung jumlah oposisi, jurnalis, dan pembela HAM telah dipantau secara digital oleh rezim otoriter dengan bantuan “kontraktor intelijen dan pengawasan swasta”.
Dan yang keempat, ekosistem komunikasi digital telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran. Karena perangkat keras digital memerlukan berbagai macam mineral serta logam berbeda. Manufaktur elektronik juga menghasilkan produk sampingan yang beracun. Yang lebih dahsyat adalah dampaknya terhadap perubahan iklim. Komunikasi global mengkonsumsi tujuh persen dari listrik dunia, dan proporsi itu dapat bertambah tiga kali lipat dalam sepuluh tahun mendatang.
Apa yang Harus Dilakukan?
Kita mungkin sependapat, bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengendalikan perkembangan tersebut. Tapi, apa?
Melakukan “isolasi mandiri” terhadap media sosial, tentu bukanlah pilihan. Karena, selain “empat kenyataan menyakitan” di atas, internet dan media sosial juga telah memberi kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan peradaban umat manusia.
Hemat kita, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, mendorong pemerintah dan DPR untuk mendugas pengesahaan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Dengan regulasi tersebut, masyarakat sipil akan terlindungi dari komersialisasi data pribadi. Selain itu, juga diharapkan adanya sebuah lembaga independen yang menjalankan undang-undang ini. Dengan otoritas (dan tentu saja anggaran yang memadai) untuk dapat membatasi tentang hal apa saja yang dapat dilakukan perusahaan (media sosial) terkait usaha mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan data pribadi (pengguna).
Yang kedua, adalah pentingnya menumbuhkan literasi digital di kalangan masyarakat pengguna (termasuk Anda dan saya). Sehingga terbit kecakapan kognitif (dan teknikal) di dalam mencari, menggunakan, membuat dan membagi konten atau informasi melalui berbagai platform media sosial. Barangkali itu!
(Imran Duse, Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur dan mantan Pemred Majalah PINISI)