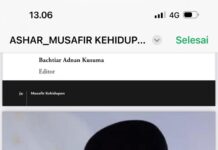Oleh Ruslan Ismail Mage
“Siapa yang akan memerintah? Kekayaan ataukah manusia. Siapa yang akan memimpin? Uang ataukah intelektual. Siapa yang akan mengisi posisi umum? Manusia bebas berpendidikan yang patriotik ataukah budak yang menghambakan diri kepada kapital perusahaan”.
Itulah inti kegelisahan Edward G. Ryan dalam pidatonya tahun 1873 di Wisconsin University, yang mengawali dengan beberapa pertanyaan menyikapi tumbuh suburnya kapitalisasi politik di Amerika Serikat. Kapitalisasi politik adalah suatu kondisi dimana penentuan jabatan-jabatan politik atau jabatan publik diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Itu berarti siapa yang memiliki modal itulah yang berpeluang menjadi pemimpin atau legislator. Moralitas, integritas, dan loyalitas ditempatkan pada anak tangga paling bawah.
Jadi kalau harus menjawab pertanyaan Edward G. Ryan di atas dalam konteks kekinian Indonesia, mungkin kita sepakat jawabannya : yang memerintah adalah kekayaan, yang memimpin adalah uang, dan yang akan mengisi posisi umum adalah budak yang menghambakan diri kepada kapitalis perusahaan. Jawaban ini mungkin tidak berlebihan, karena fakta tidak terbantahkan kalau kapitalisasi politik berkembang begitu pesat di hampir semua ruang kehidupan berbangsa negeri ini. Wilayah politik semuanya harus diukur atau dinilai serba uang, sehingga wilayah politik tak ubahnya menjadi pasar malam yang semuanya bisa ditransaksikan.
Orang yang ingin memasuki wilayah politik harus menyiapkan modal cukup banyak untuk melakukan transaksi jual beli suara di dalamnya. Dari sinilah hukum pasar bermain yang selalu berpihak kepada pemilik modal. Thomas Koten, Direktur Social Development Center mengatakan, “Demokrasi bukan lagi menjadi gelanggang fair nan suci bagi para politisi sejati untuk meraih posisi-posisi strategis dalam menjelmakan ide-ide dan gagasan politiknya yang menyejahterakan rakyat, melainkan sebagai ruang bagi para kapitalis untuk menjadi penguasa di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai areal para calo dan penjudi politik mencari peruntungan diri”.
Pidato Kepala Pengadilan (Chief Justice) dari Mahkamah Agung Wisconsin Amerika Serikat tahun 1873 ini menyuarakan kegelisahan hati dan pikiran kelompok terdidik bangsa ini pasca reformasi. Kegelisahan itu pun sangat beralasan, karena kapitalisasi politik selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi dan berbanding terbalik dengan tingkat keberpihakan kepada rakyat. Semakin tinggi biaya politik semakin tinggi peluang korupsinya, disisi lain semakin tinggi biaya politik semakin rendah tingkat keberpihakan kepada rakyat. Buya Safii Maarif pernah mengatakan, “Kalau saja agama membolehkan, saya sudah putus asah melihat perilaku pemimpin negeri ini”.
Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat korupsi. Sementara menurut peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) ada 586 anggota DPR dan DPRD ditetapkan tersangka korupsi dalam kurung waktu 2010 sampai 2019. Hal ini kembali dipertegas Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia yang mengutip data KPK bahwa ada sekitar 84% pemilihan kepala daerah dibiayai cukung. Jadi kalau tidak prihatian melihat banyaknya pemimpin daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) dan anggota parlemen terjerat korupsi, itu sudah tidak normal lagi.
Ketidak normalan itu dipicu oleh minimal dua hal. Pertama, semakin tingginya biaya politik. Kedua, hampir semua orang menganggap jabatan kepemimpinan itu sebagai arena mencari peruntungan diri, bukan sebagai arena menjalankan amanah. Yang terjadi kemudian kapitalisasi politik hanya melahirkan pemimpin bermental dealer bukan leader. Lalu apakah panggung demokrasi Indonesia salama ini belum menghasilkan leader sejati? Berikut deskripsi jawabannya.
Pajak Nol Rupiah
Sesungguhnya leader sejati tugasnya mengerucut kepada tiga hal, yaitu mengambil keputusan, menginspirasi, dan menggerakkan. Menggunakan dua tangannya untuk menciptakan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan. Tangan kanannya dipergunakan untuk tanda tangan keputusan di atas meja, sementara tangan kirinya menginspirasi, dan menggerakkan untuk melaksanakan keputusan itu. Artinya kedua tangannya bekerja di atas meja, bukan di bawah meja.
Dalam situasi kapitalisasi politik yang telah mencengkram republik kaya ini, masih adakah pemimpin di Indonesia kedua tangannya bekerja di atas meja mengedepankan transparansi untuk keadilan? Untuk mengetahuinya bisa dijelajahi jejak kepemimpinannya. Satu di antara jejak pemimpin yang mempertahankan konsistensinya sebagai leader adalah Anies Rasyid Baswedan. Berikut salah satu jejaknya yang bisa meyakinkan publik kalau Anies adalah leader bukan dealer.
Sebagai tokoh pembaharuan, Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta terus melakukan terobosan baru yang tidak pernah dilakukan pemimpin sebelumnya untuk menghadirkan keadilan. Salah satu terobosan humanisnya adalah membuat Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Peraturan ini dikeluarkan karena selama ini di Jakarta ada ketidakdilan terjadi di depan mata tentang pajak. Sebagaimana dilaporkan pajak.com yang mengutip pernyataan Anies, “Ada kecenderungan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Jakarta naik setiap tahun. Bahkan kenaikannya bisa mencapai 500 persen. Kalau ini terus dibiarkan, pelan-pelan orang nanti pada nunggak pajak, lalu ujungnya menjual tanah kepada pemilik modal”.
Menurut Anies, bayangkan kenapa rumah M. Natsir, rumah H. Adam Malik dijual? Kenapa para tokoh pendiri republik ini, pejuang kemerdekaan bangsa rumahnya di daerah Menteng satu-satu dijual? Karena tidak mampu bayar pajak. Bayangkan, mereka yang berjuang mengusir penjajah di negeri ini, lalu mereka terusir di tanah yang dibebaskan dari penjajah karena tidak bisa bayar pajak. Sama dengan yang dialami mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Brobudur pajaknya setahun Rp 180 juta, dan anak turunanya iyuran untuk membayar pajaknya. Bayangkan, seorang yang sangat banyak berjasa membangun Jakarta justru kita pajaki sebesar-besarnya.
Kondisi ini harus dihentikan, harus dirubah, jelas Anies tegas. “Semua orang yang berjasa ke republik ini, semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang harus dibebaskan pajaknya nol rupiah. Inilah ibu kota, dan saatnya ibu kota menyampaikan terimakasih dan apresiasi kesemuanya dengan cara membebaskan mereka dari Pajak Bumi Bangunan (PBB)”.
Ketika dibebaskan banyak orang berterimakasih kepada Anies, tetapi jawaban Anies, “Jangan berterimakasih kepada saya, kamilah generasi muda bangsa ini yang harus berterimakasih telah berjuang untuk bangsa ini”.
Luar biasanya lagi, bukan cuma keluarga pejuang yang dibebaskan pajaknya nol rupiah, tetapi juga semua guru dan ustadz guru ngaji yang tinggal di Jakarta dibebaskan juga pajaknya nol rupiah. Menurut Anies, “Guru juga pahlawan yang banyak berjasa ke negeri ini. Semua orang yang berjasa di republik ini tidak boleh bayar pajak. Kita tidak ingin Jakarta secara tidak sadar orang-orang yang tinggal di bawa pelan-pelan dipindahkan keluar ibu kota karena tidak mampu bayar pajak”.
Bukan hanya itu, karena Anies mengambil kebijakan untuk menghadirkan keadilan, kebijakan nol rupiah PBB juga berlaku bagi semua rumah di DKI Jakarta yang NJOP kurang dari Rp 2 miliar. Sementara, untuk rumah di atas Rp 2 miliar, 60 meter pertama juga masih nol persen, kemudian sisanya diwajibkan untuk membayar PBB.
Kalau Anies bermental dealer kebijakan pajak nol rupiah untuk keluarga pejuang, guru, ustadz, dan seluruh rumah NJOP kurang Rp 2 miliar tidak dikeluarkan. Menurut Anies, “Akibat Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 itu, 85 persen warga dan bangunan di DKI Jakarta tidak terkena PBB. Artinya ada sekitar Rp 2,7 triliun total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan pembebasan PBB, sekarang bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka.” Benar-benar untung Anies leader bukan dealer.
Penulis, inspirator dan penggerak, penulis buku-buku motivasi dan politik