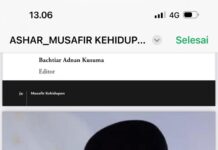Kolom Alif we Onggang
Segitu pentingnya politik, maka Pilkada serentak digelar dalam puncak pandemi. Ini karena politik adalah segalanya; ia panglima yang mengatur mati hidupnya seseorang, sejak keluar dari rahim hingga masuk ke liang kubur.
Dalam siklus lima tahunan hajat politik memilih para pemimpin, tapi setiap hari sebenarnya warga berpolitik. Apa yang diunggah di grup-grup media sosial menunjukkan identitas dan sikap politik warga: kemana afiliasi dan pandangan politiknya berlabuh.
Betapapun mungkin, tanpa disadari unggahan itu kepanjangan tangan dari sebuah kepentingan, entah dari pemengaruh (influencer), pendengung (buzzer) buat testing the water, untuk penjaringan elektoral, seperti yang kita rasakan pada setiap ajang Pilkada, Pilgub hingga Pilpres.
Dalam kondisi kusut begini, media daring yang kurang percaya diri memanfaatkan kegaduhan politik untuk menarik pembaca dengan modus clickbait. Semakin banyak klik dari pembaca, sang media diuntungkan secara finansial. Tak heran jika judul berita cenderung provokatif, atau membenturkan pendapat seorang tokoh dengan tokoh lainnya atau bahkan dengan pecundang. Dan cilakanya, pembaca sering terjerat dalam akrobatik politik murahan ini. Buntutnya, keterpecahan dan permusuhan antarwarga menambah luka baru.
Residu pilpres 2014 yang memuncak pada Pilgub DKI, telanjur membelah sebagian warga menjadi dua ekstrem. Masing-masing kutub menganggap lawannya adalah antagonis. Warga terkotak dalam ‘kekamian’ untuk menafikan ‘kekitaan’. Adalah mustahil menyeragamkan sikap politik.
Bahkan Lebih pelik lagi posisi keduanya diametral, sehingga setiap kubu berdialog dengan diri dan kelompoknya. Masing-masing ingin mendengar apa yang ia percayai dan yakini. Kebenaran cuma menjadi milik dan kelompoknya, bukan dari kelompok lain.
Acap dua kutub bertolak dari sikap apriori. Pelbagai hal dikapitalisasi dan dipolitiking. Pada simpul tengahnya kerap bertemu titik kebencian, mencari-cari kesalahan bukan menemukan dan mengupayakan kebaikan.
Tak ayal, terjadi bias kognitif. Kami putih kamu hitam. Kamu salah dan kamilah yang benar. Padahal bisa saja yang dituduh salah yang benar. Dan begitu sebaliknya. Boleh jadi dua-duanya benar, atau secara bergantian dua-duanya keliru.
Satu pihak mengaku agamis, dan pihak lain mengklaim pancasilais, kendati dua norma ini belum aplikatif dalam kehidupan kewargaan dan kebangsaan. Acapkali apa yang diomongkan berkebalikan dengan kelakukannya. Kadang beragama berhenti dalam ritual simbolik, Pancasila mandeg dalam retorika sloganistik. Tak kurang Pancasila dan agama digunakan sebagai kedok untuk melanggengkan budaya koruptif dan penjatuhan kekuasaan.
Lapisan penengah yang diharapkan dapat memoderasi, sebagian terkooptasi dengan kekuasaan, dan separuh di luarnya menjadi oposan partisan, sementara kekuatan sipil melemah dan kelompok milineal lebih tertarik pada isu lingkungan dan bisnis, sehingga di jagat virtual berseliweran narasi konservatisme, rasisme, fitnah berikut anakannya seperti sumpah serapah. Tak ada sekat antara ruang privat dan publik. Orang dengan mudah mencaki maki dan semua bersilang sengkarut dengan interes politik di tengah munculnya gejala otoritarianisme.
Meski politik pada tujuan mulianya adalah membahagiakan rakyat. Tapi pada banyak kasus, politik lebih sering menghianati orang banyak. Rakyat hanya nomor, angka, dan sewaktu-waktu namanya menjadi silang sengketa; ia bukan subyek. Harga suaranya tidak lebih dari dua bungkus rokok ‘beracun’.
Tapi itulah politik. Pengikut dua kubu boleh terus berseteru, padahal elit-elitnya bermain mata dan bergandengan tangan. Ini karena tak ada partai ideologis. Setiap saat orang bisa jadi kutu loncat dan penumpang gelap di partai. Jadilah partai oportunis-pragmatis. Di satu daerah, partai sekuler dan agamis berantem, namun di tempat lain, yang agamis dan sekuler justru berangkulan lantaran kepentingannya sama.
Lebih dari itu, politik memakai gincu dan topeng untuk menyembuyikan syahwat aslinya. Baru ketahuan wataknya setelah ia memegang kekuasaan. Syukur-syukur jika tidak diciduk KPK.
Pilkada 2020
Dalam suasana pilkada, warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di manapun berada memilih bupati, walikota, gubernur sehingga dampak baik buruknya akan kembali ke warga sendiri.
Pada era disrupsi digital dan hidup dalam pasca kebenaran, informasi mudah dipelintir dan disebar lewat media sosial, semata-mata demi raihan pengikut dan suara.
Motif politik sianre bale (saling memangsa) secara tidak langsung menimbulkan kerugian bagi semua. Kembali merebaknya politik sekretarian, politik identitas, populisme hingga pembunuhan karakter merupakan referensi publik dalam politik elektoral.
Eksploitasi dalam kepentingan politik telah menggiring terciptanya sentimen kewargaan yang berujung pada kebencian, kekerasan dan bahkan radikalisme sehingga berpotensi mencacah kesolidan yang selama ini terjaga.
Dalam pilkada serentak 2020, tidak sedikit warga KKSS ikut dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Warga KKSS sendiri terbagi dalam menentukan pilihan karena sesama warga KKSS yang bersaing.
Fatsun politik KKSS dengan tegas tidak menggiring ke salah satu calon akan tetapi memulangkan kepada hak politik masing-masing warga. KKSS non partisan dan tidak terkait pada nama, lembaga dan partai.
Daerah-daerah basis warga KKSS akan saling bersaing di mana warga KKSS sendiri saling bertarung. Kalaupun tidak, warga menjadi rebutan suara, apalagi banyak pengurus KKSS di wilayah menjadi fungsionaris partai politik.
Alhasil, kita harus belajar dari tahun-tahun politik sebelumnya, tersebab kepentingan politik telah membuat banyak masyarakat berada di persimpangan jalan. Tidak sedikit warga terjerembab dan larut dalam keberpihakan buta.
Tahu kan risiko cinta buta? Gigit jari karena tidak mendapatkan apa-apa.