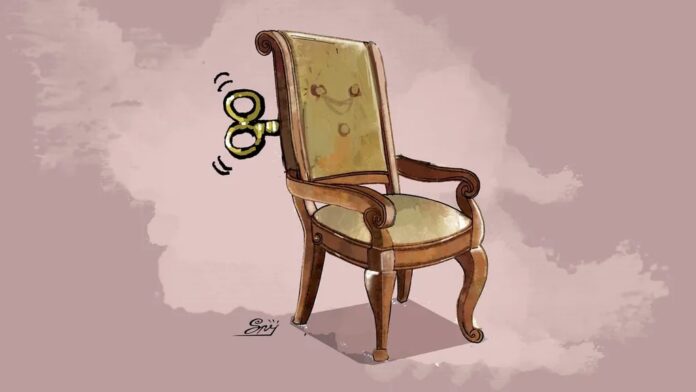Kolom Murham Ramli
Setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara, mulai dirumuskan berdasarkan kebutuhan mendesak untuk membangun negara yang baru lahir. Salah satu aspek penting dalam perjalanan tersebut adalah lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, khususnya terkait dengan otonomi daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini merupakan dasar awal yang menegaskan pembentukan daerah otonom setingkat karesidenan, kota, dan kabupaten. Otonomi yang diberikan pada masa itu disebut sebagai “otonomi Indonesia”, yakni otonomi yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini membuatnya lebih luas dibandingkan dengan otonomi daerah pada masa kolonial Belanda.
Namun demikian, jenis urusan dan wewenang daerah belum diatur secara rinci. Prinsip yang berlaku adalah bahwa daerah bebas memutuskan dan melaksanakan kebijakan selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah yang lebih tinggi. Menurut Syamsuddin Noer, pembatasan kewenangan daerah pada masa ini sangat longgar, sehingga ruang gerak daerah cukup luas.
Dalam hal pembiayaan urusan rumah tangga daerah, hampir seluruhnya ditanggung oleh daerah masing-masing, sesuai dengan kemampuan lokal. Dengan kata lain, beban keuangan sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Kebijakan otonomi saat itu lebih ditujukan untuk memperkuat konsolidasi politik dan mempertahankan kemerdekaan daripada mengembangkan kapasitas ekonomi daerah.
Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Aturan Pokok Pemerintahan Sendiri di Daerah. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mempertegas kedudukan daerah otonom. Dalam regulasi ini, terdapat tiga tingkatan daerah, yakni Provinsi, Kabupaten/Kota besar, dan Kota kecil.
Selain itu, undang-undang ini juga mengenal keberadaan daerah istimewa yang kedudukannya setingkat provinsi dan kabupaten. Pada periode ini, pembentukan daerah dilakukan bersamaan dengan penyerahan otonomi dasar (disebut urusan pangkal).
Secara umum, provinsi memperoleh kewenangan untuk mengurus 15 bidang urusan, antara lain Pemerintahan umum, Agraria, Pekerjaan umum (pengairan, jalan, dan gedung), Pertanian, Perikanan dan koperasi hingga Perdagangan dalam negeri dan perindustrian dan Perburuhan.
Sementara itu, kabupaten/kota menerima 14 bidang urusan, hampir sama dengan provinsi, namun tanpa kewenangan atas lalu lintas dan angkutan bermotor.
Dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1945, regulasi ini jauh lebih komprehensif. Sayangnya, implementasinya tidak berjalan maksimal karena kondisi politik dan keamanan nasional yang tidak stabil. Pemberontakan Madiun tahun 1948 serta agresi militer Belanda menjadi penghambat utama. Fokus pemerintah saat itu lebih banyak diarahkan pada upaya mempertahankan kedaulatan negara daripada membangun sistem pemerintahan daerah yang ideal.
Jika ditinjau dari perspektif keuangan negara, kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah pada awal kemerdekaan belum memiliki sistem pendanaan yang memadai. Daerah pada umumnya harus membiayai sendiri urusan rumah tangganya. Hal ini menimbulkan kesenjangan, mengingat kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda.
Dengan demikian, tata kelola keuangan negara pada masa itu masih bersifat sentralistis secara politik, tetapi desentralistis dalam hal beban keuangan. Pemerintah pusat lebih banyak mengatur garis besar, sementara pembiayaan menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Kondisi ini pada akhirnya mendorong lahirnya perdebatan panjang mengenai keseimbangan antara pusat dan daerah, yang terus berkembang hingga periode-periode selanjutnya.