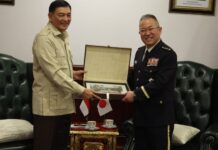Kolom Alif we Onggang
Tahun 2020 adalah periode yang kelam dalam sejarah peradaban sehingga ia cepat-cepat ingin ditinggalkan. Masa suram yang begitu menekan, tidak saja memenjarakan fisik, dan meringkus naluri dasar manusia untuk saling berkumpul akan tetapi ia juga membunuh jutaan orang.
Tak kurang, pandemi pun membekap untuk sementara syahwat manusia untuk berlaku konsumtif sebagaimana ciri hedonisme. Sebagai gejala kultural yang mewabah seperti virus korona itu sendiri, konsumerisme serta merta kehilangan gairah oleh pergerakan mahkluk tak kasat mata ini.
Sedihnya lagi, wabah Covid-19 bakal memuncak pada tahun 2021, — bahkan virus SARS-CoV-2 sebagai biang telah ribuan kali memodifikasi materi genetiknya. Ini memaksa kita menata kembali norma kehidupan melalui pelbagai adaptasi agar manusia tetap survive.
Mungkin pangkal dari semua ini karena manusia tak pernah puas pada materi di luar kebutuhan dasarnya. Sementara kapitalisme tak henti memproduksi barang agar dikonsumsi terus menerus. Kalau bisa sekali pakai buang. Adapun alam sebagai penyedia bahan baku kini kewalahan meladeni kerakusan manusia. Akibatnya hubungan alam dan manusia timpang. Ekploitasi secara berlebihan mengakibatkan bumi — sang Ibu Pertiwi terluka.
Makanlah selagi lapar dan berhentilah sebelum kenyang, itu pesan Nabi Muhammad. Bumi mencukupi kebutuhan manusia, namun tidak cukup buat yang serakah. Begitu Gandi mengingatkan. Tapi penganjur kebaikan ini tidak diindahkan.
Realitanya, tanah jadi beracun disuntik pestisida, gunung dikuliti untuk disedot emasnya, bukit karts sebagai tabungan air ditambang untuk semen. Laut dicemari mercuri dan mikroplastik. Di Indonesia, hutan lindung digunduli jutaan hektar untuk perluasan perkebunan sawit dan tanaman pangan food state yang sebenarnya selalu gagal sejak Orde Baru. Dampak sosial ekologisnya lebih mudarat ketimbang nilai keekonomiannya.
Tak terbayang, setiap menit bumi kehilangan hutan 40 kali luas lapangan bola (2017). Buntutnya bencana longsor, banjir bandang, kebakaran hutan. Semua berujung pada pemanasan global yang menyebabkan lapisan es (glaster) mencair, melenyapkan pulau, menghidupkan kembali ribuan mikroba berupa virus dan bakteri yang sewaktu-waktu dapat menginfeksi manusia, seperti halnya virus antraks.
Keserakahan tak dinyana membikin mahkluk jasad renik seperti bakteri dan virus terusik. Untuk bertahan hidup, tak ada pilihan lain, virus beradaptasi, melawan dan mengunci sel manusia seperti Covid-19 yang kini telah bermutasi dengan berbagai variannya.
Membatasi Nafsu
Sulit memang membatasi syahwat berbelanja. Sebagai konsumen, manusia memerlukan penanda, yakni status sosial guna merayakan kepuasan jasmaninya. Mulai aksesoris yang remeh temeh hingga mobil mewah, dari busana yang modis sampai jenis makanan istan yang diseruputnya. Gaya hidup konsumerisme, menjadi wadah paling menggiurkan bagi ekonomi pasar. Dan Indonesia merupakan pasar empuk dari, — mulai limbah, sampah, obat-obatan, pangan, industri hiburan, hingga produk berteknologi tinggi.
Sepintas, belanja bukan lagi sebatas untuk memenuhi kebutuhan fisikal, akan tetapi ia telah menjadi ritus sosial demi libido belanja itu sendiri. Betapa berbelanja bermetamorfosa menjadi ajang eksistensi diri. Anda adalah apa yang anda konsumsi.
Tanpa disadari budaya konsumtif telah menjadi habit. Tidak subtansial lagi, yang disantap bernutrisi atau tidak. Tapi, untuk komunikasi sosial, orang membutuhkan pengakuan dalam fase yang paling rendah, yakni kemasan dengan segala bentuk formalismenya.
Tak disangkal, banyak yang bangga menjadi konsumen produk asing. Apapun, meski mungkin barang itu telah afkir di negara asalnya.
Efek konsumtif lainnya, paralel dengan sikap boros: membeli barang yang jarang dipakai, menyalakan TV tanpa menonton, membiarkan AC hidup di ruang kosong, berkendara kendati bisa ditempuh dengan jalan kaki. Inilah bibit-bibit pemanasan bumi.
Bukti lainnya, Indonesia merupakan pembuang sampah plastik dan penyampah sisa makanan terbanyak kedua di dunia. Tak heran, kerap terlihat orang menumpuk makanan di piringnya kemudian menyisakan dua kerat daging. Padahal untuk menghasilkan satu kilogram daging, seekor sapi memerlukan 15.400 liter air dalam mata rantai proses ini.
Tapi begitulah kapitalisme bekerja. Ia memaksa orang untuk menjadi hamba sahaya. Tak jarang untuk memuaskan nafsu badaniahnya, orang melakukan korupsi.
Makin sempurna karena variabel-variabel pendukungnya seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelas menengah baru, mengubah perilaku untuk bergerak tanpa arah.
Namun, di tengah kenyamanan itu diam-diam datang virus korona yang melumpuhkan banyak aktivitas manusia.
Tatkala pandemi mengunci manusia di dunia, alam semesta kembali ke marwahnya: langit kian biru, emisi gas rumah kaca menurun, udara lebih segar, satwa, fauna, berpesta pora ke luar dari sarangnya, merasa damai seraya mengejek manusia yang terkurung diri di rumah.
Pada akhirnya, perang melawan pandemi tak pernah usai. Pasalnya, untuk bertahan hidup, virus selalu bermutasi agar variannya bereplikasi dan kian efisien ia mengifeksi kita. Kecerdasanlah yang memenangkan di antara dua makhluk Tuhan ini, manusia atau virus.
Sekiranya benar, tak terbilang banyaknya virus purba yang tidur panjang di lapisan es, akan bangkit dari kuburnya, manakala perubahan iklim dalam wujud pemanasan global tak dapat dihalau. Pun La Nina, susah payah mendinginkan suhu bumi yang memanas belakangan ini.
Wabah Covid-19 juga memberi hikmah; bahwa kolaborasi antarbangsa tereposisi kembali, demikian juga kebiasaan-kebiasaan baru tercipta berkat inovasi.
Kelak, orang hanya akan mengonsumsi produk yang ramah lingkungan, membeli barang rumah tangga hasil daur ulang, memakai kendaraan listrik, menyantap menu berbahan organik. Begitu seterusnya.
Dan tentu yang paling hakiki adalah bagaimana manusia merajut kembali relasinya dengan alam dan Sang Pencipta.