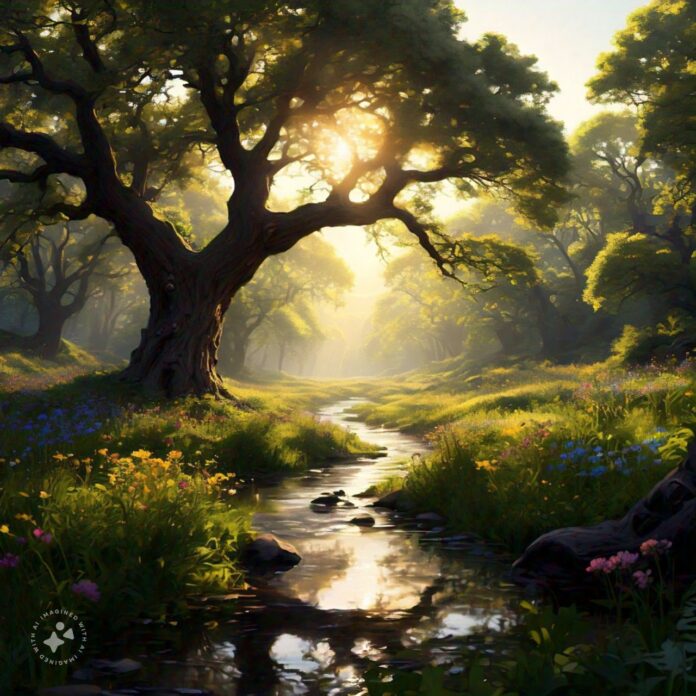Cerita Pendek Iphat Chan
“Ayi … tolong ambil tikar pandan di gudang, bawa ke teras depan. Amak mau menjemur padi.” Amak bicara dari teras depan, saat aku tengah menikmati sarapan pagi di meja makan.
Kuhabiskan teh manisku, sekalian dengan ketan dan goreng pisang. Amak selalu tahu seleraku. Setiap kali pulang dari Bogor, selalu ada sarapan khas kampung yang Amak sajikan setiap hari.
Aku bukan type anak yang suka menyanggah, walau pun dalam hati, aku tidak bisa menerima apa yang tadi disampaikan Amak. Bagaimana mungkin, Amak akan menjemur padi, sementara langit masih menyisakan rintik usai hujan semalam.
Aku mengambil tikar pandan, empat lembar dari gudang. Tikar itu digulung pada bambu setinggi dua meter. Kuletakkan di teras depan. Amak tengah menyapu tembok halaman.
“Sudah habiskah teh, goreng pisang dan ketan?” tanya Amak padaku.
“Sudah Mak. Enak. Ayi kenyang.” Aku mengusap perutku dari balik jilbab yang menutup sampai ke perutku.
Amak tertawa melihat ulahku.
“Berarti, sudah kuat untuk mengangkat padi dari gudang ke sini.” Amak bicara dengan tenang dan kemudian mengerlingkan mata beliau. Menggoda anak bungsunya yang tadi mengaku sudah kenyang. Sudah kenyang, tentunya sudah kuat.
“Eee yayai … sudah termakan pemberian Amak, tak ada lagi alasan untuk bilang tidak kuat mengangkat padi.” Aku pura-pura menggerutu sambil berlalu lagi ke gudang.
Amak tertawa lepas sambil menatapku. Beliau memang terbiasa begitu sedari dulu. Ada saja makanan yang akan beliau buat. Pisang yang sudah terlalu masak, dan tidak dilirik lagi untuk dimakan, bisa menjadi godok di tangan beliau. Racikan tangan beliau selalu enak. Setidaknya, cara Amak seperti itu, bisa mengirit pemakaian beras di rumah kami. Hasil panen sawah yang tidak terlalu luas, bisa cukup untuk makan setahun.
Jika sudah puas menikmati masakan Amak, aku dan ketiga Udaku pun siap dengan segala tugas yang akan diberikan Amak. Maklum, kami harus giat membantu Amak dengan segala usaha untuk bisa melanjutkan hidup, setelah Apak meninggalkan kami.
Beliau tidak meninggal, tapi hanya tidak pernah lagi pulang. Kami tidak bertanya pada Amak, apa sebab Apak tidak pulang. Kata Nenek, Apak ingin anak perempuan. Saat tahu Amak hamil anak ke empat, dan tukang urut mengatakan Amak hamil anak laki-laki lagi, Apak pergi.
“Kita bisa hidup tanpa Apak, jadi jangan permasalahkan lagi kepergiannya, terima ini sebagai takdir kalian. Satu hal pesan Amak, jika kelak kalian dewasa, jangan lakukan apa yang menurut kalian salah pada Apak.” Masih terngiang diingatanku, kalimat demi kalimat Amak, saat Uda Zal membahas kabar angin tentang Apak yang sudah menikah di Jakarta.
Aku selesai menyusun empat karung padi di teras, yang kubawa pakai lori. Matahari bersinar cerah. Amak menggelar tikar pandan di halaman yang sudah dicor. Kubantu Amak manghampar padi pada tikar pandan. Diatas padi yang terhampar, aku membungkukkan badan, menggoyang tangan membentuk lengkungan, seperti lengkungan pelangi, sambil berjalan mundur.
“Mak, kenapa Amak tahu, hari akan panas?” tanyaku.
“Karena semalam banyak bintang, dan Siamang berbunyi riuh dari Telaga Rahayu,” jawab Amak sambil menunjuk bukit di ujung barat kampungku.
Pagi tadi memang riuh sekali bunyi siamang, binatang primata dengan bulu hitam legam, yang di bawah dagunya, seperti ada tembolok, jika ia tengah mengeluarkan bunyi.
Uwok! Uwok! Uwok! Begitu bunyi siamang tersebut.
Dulu, aku dan Uda Hadi sering tertawa jika kami makan nasi di pagi hari. Kami jarang makan pagi, seringnya, pagi itu, makan ubi rebus atau aneka gorengan. Jika makan nasi, bisa dipastikan Amak akan memasak nasi dengan air yang banyak. Air nasi akan Amak sisihkan untuk kami minum bersama sedikit garam. Jika sedang ada kelapa, Amak akan memasukkan sedikit kelapa parut, bagian yang putihnya saja. Sereal ala Amak. Sebagian lagi, air nasinya akan dibuat sambal. Samba Uwok namanya.
Samba Uwok itu, khas kampungku, kalau dari daerah lain di Minang, sering menyebutnya Samba Cangkuak, atau Lado Kuah.
Dalam mangkuk keramik, Amak menyiapkan cabe dan bawang yang sudah digiling, serta bawang dan tombak bawang, yang sudah di iris tipis. Jika tidak ada tombak bawang, Amak akan memakai bagian pangkal daun bawang. Ditambah sedikit teri Medan, atau ebi. Diberi sedikit garam, lalu disiram dengan air nasi. Mangkuk berisi adonan tersebut akan dimasukkan lagi ke dalam Periuk yang nasinya baru saja mendidih. Ditutup sampai nasi matang. Biasanya akan ada sayuran yang hanya direbus, atau ikut dimasak dalam nasi. Labu siam, atau buncis, dan sesekali terong atau kacang panjang.
Lain waktu, Amak kadang membuatnya dengan memasukkan cabe bulat, tomat dan bawang bulat yang sudah dikupas. Air nasinya disisihkan dalam wajan. Cabe, bawang dan tomat yang sudah matang, digiling, dimasukkan ke dalam wajan berisi air nasi, lalu diberi potongan daun bawang, dan sedikit minyak, juga sum-sum dari dalam tulang sapi. Ini hanya sesekali kami makan, sum-sum tulang sapi hanya ada jika lebaran haji, atau jika Amak ke Pasar Bawah di kota Bukittinggi.
Hampir setiap kali makan itu lah, kudengar teriakan Siamang dari Telaga Rahayu. Jika aku tidak acuh, karena fokus pada lezatnya masakan Amak, biasanya Uda Hadi akan mencolekku, dan memberi isyarat apa yang diserukan Siamang.
Dulu, aku pernah menangis, karena jika makan pagi, Amak hanya menyediakan menu tersebut. Saat sedang menangis, Uda Hadi bercerita padaku.
“Ssstt … tau ndak, masakan Amak ini lezat, aromanya sampai ke Telaga Rahayu, dengarlah apa kata Siamang tu, Uwok … uwok … Uwok … katanya. Mereka mau juga … cepatlah habiskan, sebelum Siamang itu datang dan mengambil makanan kita.”
Aku mendengarkan bunyi Siamang, ternyata benar. Aku pun dengan cepat menghabiskan nasiku, takut jika Siamang datang dan memakan nasiku.
Lama kelamaan aku mengerti, itu hanya cerita bujukan Uda Hadi. Kami selalu tertawa setiap ada menu yang sama, menertawakan ketidak mengertianku dulu, juga menertawakan kondisi hidup kami sendiri.
Belakangan, Amak bercerita, dulu Amak memasak nasi, hanya di pagi hari yang ada bunyi siamang, karena Amak tidak ingin kami kelelahan saat di sekolah, dan ketika pulang ke rumah dengan berjalan kaki, saat hari panas terik. Rumah kami jauh dari sekolah, apa lagi SMP. Sekitar empat kilo meter, dan itu ditempuh setiap hari dengan berjalan kaki.
Jika Siamang berbunyi, bersahutan di pagi hari, itu tanda akan panas sampai lewat waktu Zuhur. Tanda lainnya, adalah banyak sarang laba -laba kecil di bagian permukaan hamparan daun padi, di sawah.
***
Usai shalat Zuhur, Amak ke halaman. Beliau menginjak padi di pinggiran tikar dengan tumit beliau. Tumit Amak memutar bolak-balik sebanyak tujuh kali. Amak berjongkok, dan memungut padi yang tadi diinjak Amak. Padi itu telah mengelupas. Amak mengambil berasnya dan mengunyah beras tersebut. Aku mendengar bunyi yang garing saat menghampiri Amak.
“Sudah Masiak, Mak?” (Sudah kering, Mak?) tanyaku sambil berjongkok dan mengulurkan tangan pada Amak.
“Alah.” (Sudah). Amak menjawab sambil menyerahkan beberapa butir beras padaku. Malas mengunyah, aku hanya mematahkan beras. Keras. Ini tandanya beras akan keluar utuh, tidak sumbing, tidak patah-patah saat digiling pada heler di ujung desa. Nasinya juga akan bagus, berderai. Kesukaan keluarga kami.
Amak menatap ke langit. Beberapa kelompok burung layang-layang memutar di udara tidak jauh dari halaman rumah kami.
“Angkat saja dengan tikarnya, nanti di teras baru kita masukkan ke karung,” kata Amak.
Aku tidak membantah, kuikuti saja apa kata Amak. Beliau pasti punya perhitungan sendiri.
Tepat saat tikar terakhir sampai di teras, angin berhembus kencang sekali, langit gelap, padahal sebelumnya awan gelap itu jauh arah ke barat.
Saat memasukkan padi ke karung, Amak bercerita padaku. Tentang pentingnya membaca tanda alam. Kata Amak, jika sudah banyak burung layang-layang di udara, segera angkat padi dan jemuran, meski pun hari masih tampak cerah. Karena itu adalah pertanda akan turun hujan.
“Siapa tau burungnya mau cari makan, Mak.” Aku sedikit berseloroh pada Amak.
“Elang yang berputar memang sedang mencari makan, lain dengan burung layang-layang, jika mencari makan, mereka akan terbang lurus, mereka sudah tahu dimana makanannya. Sama seperti petani yang sudah tahu letak sawah garapannya. Elang itu, makannya menyambar, seperti copet, putar kiri, putar kanan, kalau nampak induk ayam lengah, anaknya langsung di sambar elang.” Amak bercerita diikuti gerakan tangan beliau. Aku merasa seperti jadi anak kecil lagi saat melihat dan mendengar Amak bercerita.
Amak tiba-tiba diam dan membelakangiku, beliau menggosok mata dengan ujung jilbabnya.
“Amak kenapa?” tanyaku.
“Amak takut, kamu di gungguang alang,” jawab Amak.
Digungguang Alang, maksudnya disambar elang dan dibawa pergi. Jika kalimat ini disampaikan pada anak perempuan dalam hal jodoh, maksudnya si anak akan diambil orang dan dibawa pergi jauh.
Kutarik napas dalam dan melepasnya perlahan, meregang tubuh yang sedikit lelah karena kerja merunduk sedari tadi.
“Takkan jauh jodoh anak Amak.” Aku meyakinkan Amak sambil menggenggam tangan Amak.
“Sudah ada calon?” tanya Amak. Aku mengangguk.
“Siapa?” tanya Amak.
“Yang pulang bersama Ayi kemarin, Mak. Itu jika Anak setuju.” Aku menggenggam tangan Amak dengan erat.
Amak memelukku penuh haru. Berkali-kali Amak mencium pipi dan dahiku. Air mata haru Amak berderai. Seperti air di Aia Ma Ambau. Sebuah air terjun yang deras di hutan kampungku.
“Amak sih … hanya pandai membaca tanda alam, tidak mengerti dengan sinyal dari hati anak, Amak.” Kugamit tangan Amak dan bersandar di lengan beliau yang selalu kokoh.
“Orang kini, mana mau menikah dengan anak Mamaknya. Apalagi kamu, sudah kuliah ke Bogor, sudah merantau sedari tamat SMA, pastilah pikirannya maju, mencari jodoh juga orang jauh.” Amak menjawab sambil mata beliau menatap bulir hujan di depan kami, bulir hujan itu saling berpacu menuju bumi.
Seminggu yang lalu, aku pulang satu pesawat dengan Da Hasbi, anak Engku Rajo Lelo, Uda tertua Amak. Ongkos pun, Uda Hasbi yang membayarkan. Selama di Bogor, Uda Hasbi yang bekerja di Bandung, sering pesan minta dibuatkan masakan kampung. Pesanannya, selalu bertambah setiap akhir Minggu, Uda menjual hasil masakanku pada kawan-kawannya. Ini sangat membantuku dalam mencukupi kebutuhan kuliah, tanpa harus tiap sebentar meminta pada Da Zal, da Hadi dan Da Andi.
Hujan kian deras, aku bangkit untuk mengikat karung padi, dan selanjutnya menelpon pemilik heler untuk menjemput padi ke rumah.
” Tanaklah nasi, agak banyak. Buat gulai jangek (kulit sapi/kerbau) pakai kacang puyuh. Nanti Engku Rajo akan kemari dengan Hasbi dan Amaknya!” Amak bangkit dari duduk beliau dan menggulung tikar pandan.
Aku kaget dan menatap Amak tak percaya. Amak tersenyum penuh arti.
“Tanda alam saja bisa Amak baca, apalagi tanda anak gadis yang jatuh cinta. Dari usai hari raya tahun kemarin, setiap Amak menelpon, kan hanya Hasbi yang sering kamu ceritakan. Begitu juga Hasbi ketika bercerita dengan Ayahnya. Alam seseorang itu, adalah apa yang dicintainya. Jika seseorang mencintai Rasulullah, lidahnya tidak akan luput dalam sehari itu, diluar waktu shalat untuk bershalawat. Jika seseorang jatuh cinta, yang akan dia ceritakan itu, adalah apa yang dia cintai.” Amak memberi uraian panjang lebar, menjawab segala tanya di kepalaku.
Wajahku terasa panas, malu rasanya saat Amak tahu jika aku memang menyimpan rasa pada Uda Hasbi. Aku segera melangkah masuk ke dalam rumah, tak ingin Amak melihat wajahku yang terasa panas, mungkin juga memerah seperti kepiting rebus. Amak memang pandai membaca segala tanda.
***
Sarolangun, 2 Februari 2021
Catatan.
Apak : panggilan pada Ayah
Amak : Panggilan pada Ibu
Engku : Panggilan pada saudara laki-laki Ibu.