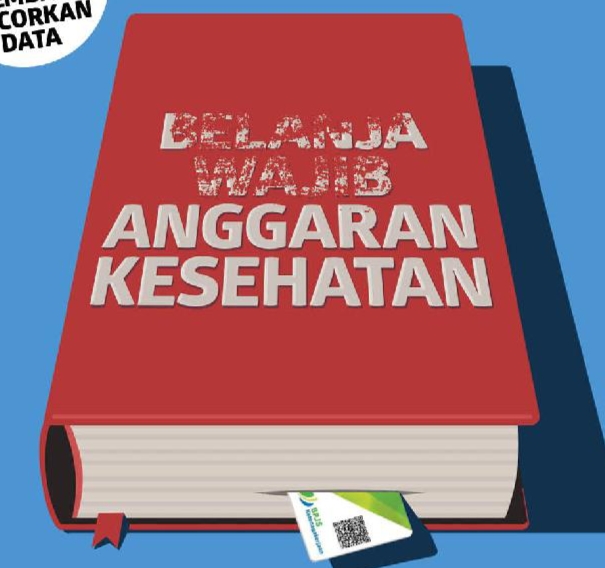Kolom Zaenal Abidin
Ditiadakannya mandatory spending di dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, hingga kini masih menjadi diskursus yang menarik di kalangan organisasi profesi dan praktisi kesehatan. Cukup banyak webinar yang diadakan untuk membahas masalah ini.
Memang cukup mengagetkan sebab ketika pembahasan masih di Badan Legislatif (Baleg) DPR, mandatory spending masih ada. Masih jelas tercantum alokasi anggaran minimal 5% APBN dan minimal 10% APBD untuk kesehatan di luar gaji pegawai, sebagimana Pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009. Namun setelah pembahasan dialihkan kepada Komisi IX DPR RI, mandatory spending kesehatan telah terhapus di dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Kementerian Kesehatan.
Menurut Menteri Kesehatan penghapusan mandatory spending dilakukan lantaran selama ini belanja wajib sebesar 5% untuk kesehatan tidak berjalan baik. Justru rawan disalahgunakan untuk program-program yang tidak jelas. Pengalaman pemerintah mengenai mandatory spending itu tidak 100 persen mencapai tujuannya, https://www.cnnindonesia.com, 19 Juni 2023.
Pada kesempatan lain Menteri Kesehatan juga menjelaskan tujuan perhapusan itu agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan besaran alokasi, melainkan berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah. Dengan demikian kata Menteri Kesehatan, program strategis tertentu di sektor kesahatan bisa berjalan maksimal.
Penjelasan Menteri Kesehatan dii atas, sontak memunculkan tanggapan dari kalangan profesi kesehatan. Sebahagian besar sangat khawatir, sebab komitmen pemerintah itu dapat saja berbeda-beda, terutama Pemerintah Daerah (Pemda). Ada Pemda yang memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap program kesehatan dan hak kesehatan rakat, namun ada pula yang masih rendah.
Karena itu, meniadakan mandatory spending sangat berisiko tidak terpenuhinya hak kesehatan rakyat dan juga berpotensi gagalnya pemerintah mengemban amanat Pasal 28H ayat (1). Bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Peniadaan mandatory spending juga berpotensi menjerumuskan Presiden untuk melanggar Ketetapan (TAP) MPR RI No. 10 Tahun 2001. Pada poin 5a angka 4 TAP MPR 2001 tesebut tercantum amanat, “Mengugaskan kepada Presiden untuk mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan sebesar 15% APBN.” Dalam amanat tersebut dibagi menjadi minimal 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan di luar gaji pegawai.
Diskursus Tebatas Soal UKP
Dalam hubungannya dengan peniadaan mandatory spending ini, awalnya perdebatan di berbagai webinar lebih terfokus pada pelayanan kesehatan di sektor hilir, yaitu pelayanan medis atau upaya kesehatan perorangan (UKP). Hal ini dapat dimaklumi sebab, peserta webinar sebahagian besar pengurus dan anggota dari lima organisasi profesi kesehatan (IDI, PDGI, IAI, PPNI, dan IBI).
Pembicaraannya, lebih banyak terkait pelayanan medis di fasyankes (FKTP dan FKTL) serta pemerataan fasyankes. Pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan (terutama dokter spesialis yang sejak awal diwacanakan oleh Menteri Kesehatan), pengadaan dan distribusi alat kesehatan, pengadaan dan distribusi obat dan vaksin, dan pembayaran gaji peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang juga dijanjikan oleh Menteri Kesehatan.
Hal lain yang juga cukup mendapat perhatian, yakni anggaran penerima bantuan iura (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan (JKN). Mengapa anggaran PBI menarik perhatian? Sebab seringkali pemerintah tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk PBI ini. Akibatnya, Pemerintah mengambilkannya dari dana mandatory spending kesehatan yang ada di APBN dan APBD.
Tarulah misalnya Kementerian Kesehatan tidak ada masalah karena telah memiliki banyak sumber anggaran, sehingga tidak membutuhkan alokasi anggaran dari APBN. Namun, bagaimana dengan PEMDA? Bila tidak tercantum di dalam APBD, darimana Pemda mau mengambil anggaran?
Bila Pemda tidak mempunyai pundi-pundi selain dari APBD, bagaimana ia dapat membayar iuran PBI yang menjadi tanggung jawabnya? Jika Pemda tidak melunasi iuran PBI kepada BPJS Kesehatan, bagaimana pesertanya dapat memperoleh layanan kesehatan yang bersinambung dari fasyankes?
Diskursus Bergesar dari UKP ke UKM
Setelah Menteri Bappenas RI melaporkan “Rapor Merah” Menteri Kesehatan akibat tidak tercapainya target RPJMN Kesehatan (/https://katadata.co.id, 5 Juni 2023), mulailah diskursus beralih topik secara perlahan dari isu pelayanan medis (UKP) ke pelayanan UKM. Mengapa? Sebab, ternyata dari 10 program kesehatan di RPJMN tersebut, sembilan di antaranya tidak mencapai target.
Mulai dari imunisasi dasar lengkap bayi, stunting balita, wasting balita, tuberkulosis, malaria, kusta, merokok pada anak, FKTP, puskesmas, dan obesitas penduduk dewasa. Dilaporkan bahwa baru program penurunan obesitas dewasa yang mencapai terget.
Diskusi menjadi makin menarik sebab, sekalipun terdapat mandatory spending di APBN dan APBD, namun target RPJMN tidak tercapai juga. Bagaimana pula nanti dengan berlakuknya UU N0. 17 tentang Kesehatan 2023, yang meniadakan mandatory spending tersebut?
Dan untuk diketahui, program kesehatan yang ada di RPJMN adalah termasuk program UKM, yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Karena itu anggarannya bersumber dari dana pemerintah. Berbeda dengan program UKP, pembiayaannya lebih banyak bersumber tanggung jawab individu penduduk. Namanya saja upaya kesehatan perorangan.
Terkait dengan program UKM dan peniadaan mandatory spending sindonews.com, 9 Agustus 2023, telah memuat artikel penulis dengan judul “Sisi Buram Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tanpa Mandatory Spending.” Penulis mengajukan 15 program UKM yang terancam gagal dengan ditiadakannya mandatori spending ini. Mengapa buram dan terancam gagal? Sebab, sumber anggaran dari program UKM tersebut bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah.
Kelima belas program di atas, yaitu: pengentasan penyakit menular dan kesiapan menghadapi edipemi dan pandemi, penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, gizi seimbang, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja, kesehatan veteriner, olahraga teratur dan rekreasi, kantin sehat serta ruang beribadah dan ruang istirahat sehat, dan juga ruang terbuka hijau tak berbayar untuk publik.
Poin berikutnya, cuti hamil dan menyusi, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), air bersih dan udara bersih, kesehatan sosial dan patologi sosial, kesehatan masyarakat berkebutuhan khusus, kepemimpinan kesehatan masyarakat. Semuanya membutuhkan alokasi anggaran kesehatan masyarakat yang jelas.
Catatan Akhir
Mandatory spending sangat penting untuk penyediaan anggaran kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi. Dan juga teralokokasi secara adil, termanfaatan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar mampu meningkatkan derajat kesehatan rakyat setinggi-tingginya.
Pencantuman mandatory spending di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan bentuk konkret dari keberpihakan awal pembentuk undang-undang kepada pembangunan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu mandatory spending adalah bagian yang amat penting bagi UU Kesehatan.
Dan, menjadi amat penting karena ketersediaan dana untuk melaksanakan upaya kesehatan sangat bergantung kepada amanat yang tertulis di dalam undang-undang. Bahwa ada sebahagian orang yang khawatir bila kelak mandatory spending disalahgunakan oleh penyelenggara atau menimbulkan pemborosan anggaran, hemat penulis pendapat tersebut agak keliru.
Sebab, bukankah penyimpangan tersebut dapat dicegah dengan mekanisme pengawasan dan program revolusi akhlak yang telah diajalankan oleh pemerintah. Apalagi bila program kesehatan tersebut dibuat dengan perencanaan yang baik serta penganggaran yang terukur, tentu semakin sulit disalahgunakan. Wallahu a’lam bishawab.
Penulis adalah Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, periode 2012 – 2015, Ketua Departemen Kesehatan BPP KKSS